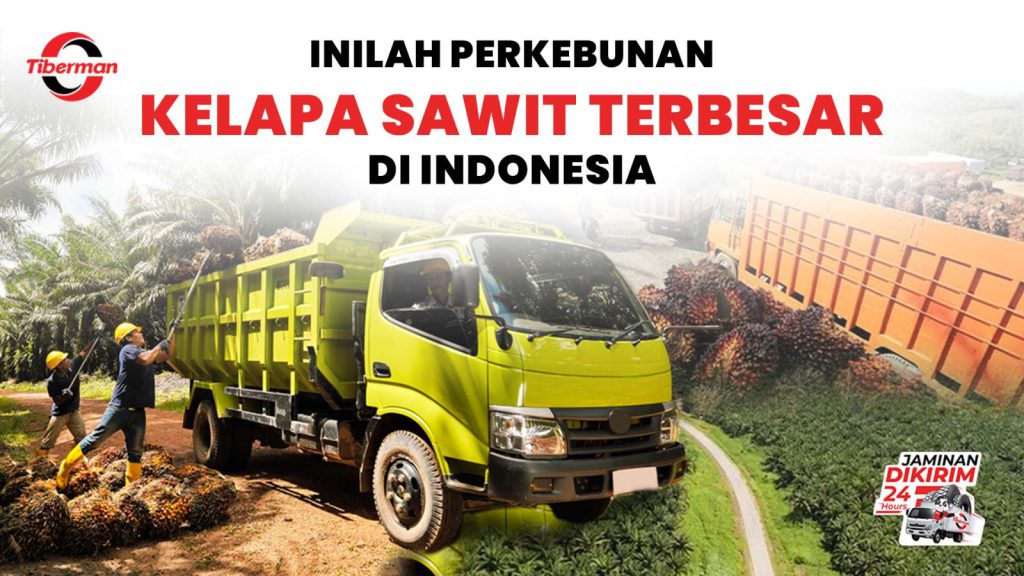Dari Mana Kelapa Sawit Berasal? Begini Sejarahnya – Kelapa sawit, salah satu komoditas terbesar di Indonesia selain batu bara dan menjadi penopang pendapatan negara. Kini kelapa sawit bukan hanya dilihat sebagai penghasil minyak goreng atau margarin saja, tetapi juga sumber energi terbarukan. Bahkan, dengan tingginya permintaan kelapa sawit di Indonesia maupun di dunia, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit juga semakin gencar dilakukan.
Indonesia sebagai penghasil CPO (Crude Palm Oil) atau minyak mentah kelapa sawit terbesar nomor 1 di dunia, jauh melampaui Malaysia yang berada di posisi kedua, tentunya memiliki perkebunan yang sangat luas untuk menghasilkan produksi sebesar itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia yang bisa memproduksi CPO sebanyak itu sebenarnya memiliki varietas kelapa sawit dari mana? Bibit-bibit yang ditanam tentunya merupakan varietas unggul untuk mengurangi kemungkinan gagal panen. Selain itu, sebenarnya dari mana kelapa sawit berasal dan bagaimana sejarahnya hingga akhirnya berkembang menjadi komoditas utama dunia saat ini?
Tiberman sebagai supplier ban alat berat yang selalu bersinggungan dengan industri kelapa sawit akan membahas sejarah kelapa sawit, dari mana asalnya, dan bagaimana akhirnya menjadi berkembang sebesar sekarang.
Sejarah Kelapa Sawit
Kelapa sawit (Elaeis guineensis) berasal dari Afrika Barat hingga barat daya, terutama di sepanjang pantai selatan Atlantik antara Angola dan Gambia. Tanaman ini telah dimanfaatkan manusia sejak ribuan tahun lalu—bukti arkeologis menunjukkan keberadaannya di Mesir kuno sekitar 3000 SM—dan didomestikasi secara bertahap melalui praktek semi-liar di wilayah hutan. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kolonialisasi Eropa membawa kelapa sawit ke Jawa (1848) dan Malaya (1910), meletakkan dasar bagi ekspansi besar-besaran di Asia Tenggara hingga menjadi komoditas minyak nabati terpenting di dunia.

1. Asal Botani
Elaeis guineensis, yang dikenal sebagai African oil palm, adalah spesies palma monokotil yang tumbuh alami di wilayah hutan dataran rendah tropis basah dan semi-kering di Afrika Barat dan barat daya. Habitat alaminya meliputi kawasan antara Angola dan Gambia—nama spesies “guineensis” mengacu pada wilayah Guinea, bukan negara modern Guinea sekarang—di mana pohon ini tumbuh sebagai pionir pada area yang baru terganggu atau dibuka untuk ladang dan pertanian.
Menurut Britannica, kelapa sawit dibudidayakan secara ekstensif di Afrika Barat dan Tengah sebelum penyebarannya ke Asia, menandakan peran pentingnya dalam ekosistem dan ekonomi lokal sejak dulu.
2. Domestikasi Awal
Proses domestikasi kelapa sawit dimulai di pantai selatan Atlantik Afrika Barat, di mana masyarakat prasejarah mengekstraksi buah dari pohon liar. Ketika hutan dibuka untuk pertanian berpindah, pohon sawit liar kerap dibiarkan hidup, lalu berkembang biak di area regenerasi hutan, membentuk kebun semi-liar (“semi-wild groves”) yang menjadi cikal bakal tanaman budidaya.
3. Bukti Arkeologi dan Sejarah Awal
- Mesir Kuno (3000 SM): Penemuan sisa minyak sawit di makam Abydos menunjukkan bahwa kelapa sawit telah digunakan sebagai bahan baku minyak lebih dari 5.000 tahun lalu.
- Dokumentasi Prasejarah di Ghana: Sebuah riset yang dipublikasikan di Springer menunjukkan analisis polen dari situs arkeologi Kintampo di Ghana Tengah mengindikasikan peningkatan mendadak keberadaan polen kelapa sawit pada akhir Holosen, mengindikasikan aktivitas manusia dalam budidaya pohon ini sekitar ribuan tahun sebelum masehi.
4. Penyebaran Global
- Jawa (1848): Biji kelapa sawit pertama kali diperkenalkan ke Jawa oleh kolonialis Belanda pada 1848, untuk ditanam di kebun eksperimen.
- Malaya (1910): Scotsman William Sime dan Henry Darby membawa bibit sawit ke Semenanjung Malaya—cikal bakal industri kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia yang kini mendominasi produksi dunia.
Setelah itu, kelapa sawit menyebar ke berbagai wilayah tropis, termasuk Sri Lanka, Amerika Tengah, dan Kepulauan Pasifik, menjadikannya tanaman minyak nabati paling produktif per hektarnya di dunia.
Penyebaran dan Perkembangan Kelapa Sawit di Indonesia
1. Masa Kolonial Belanda (1848–1945)
Kelapa sawit (Elaeis guineensis) seperti yang sudah dijelaskan di atas, bukan tanaman asli Indonesia. Lantas bagaimana awalnya bisa masuk ke Indonesia? Jawabannya dimulai pada tahun 1848 Dr. D. T. Pryce membawa empat biji kelapa sawit dari Bourbon dan Amsterdam untuk ditanam di Kebun Raya Bogor, yang tumbuh subur dan menjadi cikal bakal distribusi benih ke Pulau Sumatra.
Eksperimen penanaman selanjutnya berlangsung di Banyumas (1856–1870) dan Palembang (Mus i Ulu 1870), namun baru pada 1911 perkebunan komersial pertama dibuka oleh Adrien Hallet di wilayah Deli (Sumatra Utara) dan Sungai Liat (Aceh), dengan luas awal sekitar 5.123 ha. Perkebunan-perkebunan besar Belanda lalu berkembang pesat hingga 1937, saat luas tanam mencapai ~75.000 ha dan produksi CPO melonjak dari 181 ton (1919) menjadi 190.627 ton (1937).
2. Masa Pendudukan Jepang dan Pasca-Kemerdekaan (1942–1960an)
Setelah dibuka kran budidaya kelapa sawit oleh Belanda, ternyata pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), muncul kemunduran tajam. Luas lahan menyusut hingga 16% dan produksi CPO turun dari ~250.000 ton (1940) menjadi 56.000 ton pada 1948/49.
Akhirnya setelah Proklamasi, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih kebun-kebun asing (pada 1957) dan memulai kebijakan pembukaan lahan baru untuk pertanian, menandai fase awal transisi dari perkebunan kolonial ke sistem nasional.
3. Program Perkebunan Inti Rakyat & Transmigrasi (1978–1990an)
Mulai 1978, skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR) diperkenalkan—inti (nucleus) dikelola perusahaan, plasma (rakyat) sebagai petani plasma—dan dikembangkan lewat berbagai pola termasuk PIR-Lokal dan PIR-Transmigrasi untuk memperluas lahan kelapa sawit rakyat di daerah transmigrasi.
Skema ini didukung pembiayaan Bank Dunia, ADB, dan pemerintah Jerman Barat sehingga pada dekade 1980-an lahannya tumbuh puluhan ribu hektar, memberdayakan petani lokal serta transmigran hingga mencetak petani sawit terampil dari “Sabang sampai Merauke”. Hingga saat ini, skema PIR ini terus berlanjut, bahkan di perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia semuanya menggunakan skema ini dalam perkebunan kelapa sawitnya.
4. Ekspansi & Diversifikasi (2000an–2020an)
Di era awal 2000-an, investasi asing atau FDI dan swasta terus menambah luas perkebunan besar swasta (PBS), sementara petani plasma dan swadaya mengelola lahan di sekitarnya. Berdasarkan data dari Katadata Green, Pemerintah juga memberlakukan program peremajaan sawit rakyat sejak 2016 untuk mengganti pohon tua—hingga akhir 2023 baru ~326.308 ha disetujui dan 205.524 ha telah diremajakan. Seiring itu, skema sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mulai diadopsi oleh perusahaan besar dan beberapa kelompok petani plasma untuk menjawab tuntutan pasar global akan produk berkelanjutan.
5. Kondisi Terkini & Statistik (2022–2023)
Per 2022, Indonesia menjadi produsen CPO terbesar dunia dengan luas areal ~16,83 juta ha dan produksi ~46,82 juta ton CPO. Dari data GoodStats Data, sentra utama produksi CPO dalam negeri berada di Riau (3,40 juta ha), Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Jika ditinjau dari komposisi areal menurut status pengusahaan (2023), maka persebarannya adalah PBS ~51,1% (8,60 juta ha), perkebunan rakyat ~37,4% (6,29 juta ha), dan PBN ~3,2% (0,55 juta ha). Produksi 2023 mencapai ~46,99 juta ton, naik 0,36% dari tahun sebelumnya.
Tantangan & Prospek Kelapa Sawit Indonesia
- Peremajaan Lahan: Hambatan administratif dan tumpang tindih kawasan hutan memperlambat peremajaan sawit rakyat via BPDPKS.
- Sertifikasi & Keberlanjutan: Penerapan ISPO/RSPO masih terbatas pada perusahaan besar; perlu percepatan akses bagi petani kecil.
- Kebijakan Biodiesel (B30/B40): Mandat penggunaan minyak sawit sebagai campuran biodiesel mendorong penyerapan CPO domestik, namun menuntut kualitas dan stabilitas pasokan.
- Teknologi & Efisiensi: R&D varietas unggul, precision agriculture, dan digitalisasi menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas tanpa menambah buka lahan baru.
Berawal dari tumbuhan yang berasal dari negeri jauh antah berantah, kemudian dibawa oleh Belanda ke dalam negeri, akhirnya kelapa sawit kini menjadi komoditas strategis sekaligus menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks. Ke depan, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan petani kecil—dengan prinsip keberlanjutan—akan menjadi kunci mempertahankan peran Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia. Apalagi dengan narasi kelapa sawit dapat digunakan untuk menghasilkan energi terbarukan berupa biodiesel, tentunya Indonesia akan menjadi pemain inti di kancah global.
Berkembangnya suatu industri pastilah akan diikuti oleh industri lain yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung. Industri alat berat yang bersinggungan langsung dengan perkebunan sawit tentunya akan naik permintaannya. Kebutuhan akan truk, traktor, loader, grader, dan alat berat lain yang berhubungan dengan perkebunan akan ikut naik seiring dengan naiknya industri kelapa sawit. Selain alat berat, ada lagi suku cadang seperti ban alat berat yang akan banyak dibutuhkan di industri. Ban truk, ban traktor, ban loader, dan ban grader tentu saja banyak dicari.
Dapatkan Ban Alat Berat untuk Perkebunan Sawit hanya di Tiberman
Segera hubungi sales online Tiberman untuk mendapatkan penawaran harga terbaik.